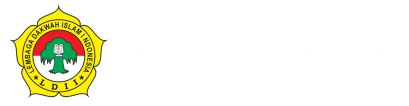LDII Aceh – Setiap kali layar ponsel dibuka, dunia seakan menjerit meminta perhatian. Judul sensasional, potongan video penuh amarah, komentar pedas yang saling menikam, semuanya hadir silih berganti. Tanpa sadar, jari kita ikut menari, mengomentari, membagikan, bahkan ikut marah. Media sosial yang awalnya diciptakan untuk mendekatkan yang jauh, justru sering menjauhkan yang dekat. Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan siapa, kita atau algoritma?
Media sosial hari ini tidak lagi netral. Ia digerakkan oleh algoritma, sebuah sistem yang bekerja membaca kebiasaan pengguna, apa yang ditonton, disukai, dikomentari, dan dibagikan. Algoritma tidak memiliki akhlak, tidak pula mengenal benar dan salah. Tujuannya sederhana, membuat pengguna betah selama mungkin di dalam aplikasi. Semakin lama seseorang bertahan, semakin besar keuntungan yang diraih platform. Maka jangan heran jika konten yang memicu emosi marah, benci, takut, dan iri, lebih cepat viral dibandingkan pesan yang menyejukkan.
Inilah rahasia kegaduhan di media sosial. Konten yang mengandung konflik, perdebatan, dan kontroversi cenderung mendapat respons tinggi. Algoritma membaca itu sebagai “menarik” lalu menyebarkannya lebih luas. Akibatnya, pernyataan yang memecah belah sering kali tampil lebih dominan dibandingkan nasihat yang lembut. Tanpa disadari, kita sedang diarahkan untuk saling berhadap-hadapan, bukan saling memahami.
Masalahnya, banyak pengguna yang terjebak dalam permainan ini. Demi validasi berupa like, share, dan komentar, orang rela mencaci, memfitnah, bahkan membuka aib sesama. Foto dan video seseorang diviralkan tanpa izin, dipelintir tanpa klarifikasi, lalu dihakimi oleh publik yang merasa paling benar. Padahal, dalam nilai agama dan etika sosial, menjaga kehormatan orang lain adalah prinsip yang tidak boleh ditawar. Apa jadinya jika kesalahan kecil seseorang menjadi konsumsi jutaan mata, sementara pintu taubat dan perbaikan justru ditutup rapat?
Lebih dari itu, kegaduhan yang terus dipelihara akan melahirkan perpecahan. Media sosial berubah menjadi arena permusuhan, kelompok ini melawan kelompok itu, pendapat dibalas hujatan, perbedaan disulut menjadi kebencian. Ukhuwah runtuh, empati menipis. Kita lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan, keluarga, dan kehidupan nyata yang terdampak.
Namun, media sosial sejatinya bukan musuh. Ia hanyalah alat. Pisau bisa melukai, tetapi juga bisa digunakan untuk menyiapkan makanan. Semua bergantung pada tangan yang memegangnya. Di sinilah peran kesadaran menjadi kunci. Memahami cara kerja algoritma berarti kita tidak mudah terpancing. Tidak semua yang viral perlu dikomentari. Tidak semua yang memancing emosi harus ditanggapi. Kadang, diam adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi.
Lebih jauh, media sosial justru dapat menjadi sarana dakwah dan penyebaran kebaikan. Pesan-pesan yang menenangkan, ajakan berbuat baik, konten edukatif, dan keteladanan akhlak tetap memiliki tempat, asal disampaikan dengan konsisten dan ikhlas. Mungkin tidak selalu viral, tetapi dampaknya bisa lebih dalam dan bertahan lama. Satu unggahan yang menyejukkan bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang gelap hatinya.
Dakwah di era algoritma menuntut strategi sekaligus keteguhan akhlak. Mengajak tanpa memaksa, menasihati tanpa menghakimi, berbeda tanpa mencaci. Media sosial bukan medan perang argumen, melainkan ladang amal digital. Setiap tulisan, komentar, dan unggahan akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi juga di hadapan Allah.
Karena itu, sebelum menekan tombol “bagikan”, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri: apakah ini membawa manfaat atau justru mudarat? Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Apakah ini menebar kebaikan atau menyulut kebencian? Dengan kesadaran seperti ini, kita tidak akan mudah terjebak dalam permainan algoritma yang haus kegaduhan.
Menguasai media sosial bukan soal mengikuti arus viral, melainkan mampu berenang melawan arus demi menjaga nurani. Ketika kita memilih untuk menahan diri dari perdebatan sia-sia, menolak mencaci, dan enggan memviralkan aib orang lain, saat itulah kita menang, bukan atas orang lain, tetapi atas diri sendiri. Media sosial pun kembali ke fitrahnya, sebagai jembatan kebaikan, bukan jurang perpecahan.